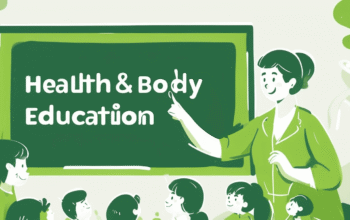Saya sudah lebih dari 20 tahun bertani di lahan milik sendiri. Setiap pagi sebelum matahari terbit, saya dan istri sudah berada di sawah. Musim tanam dan musim panen kami lalui dengan susah payah. Tapi satu hal yang tak pernah berubah: harga hasil panen kami selalu murah, sementara harga pupuk dan pestisida terus naik.
Kami para petani sering disebut sebagai tulang punggung ketahanan pangan nasional. Tapi dalam kenyataannya, kami justru seperti berada di urutan paling bawah dalam rantai ekonomi pertanian. Ketika hasil panen melimpah, kami senang—tapi justru harga turun drastis karena pasar kebanjiran stok. Saat panen gagal karena cuaca, kami rugi dua kali: kehilangan hasil dan tetap harus membayar utang modal.
Pemerintah memang punya banyak program untuk membantu petani, tapi di lapangan, bantuan itu sering tak terasa. Pupuk subsidi langka, bibit bantuan kualitasnya rendah, dan pelatihan yang diberikan terlalu teoritis. Yang menikmati program justru para tengkulak atau orang yang tidak benar-benar bertani.
Kami juga bingung mengapa hasil tani dari luar negeri bisa masuk dengan mudah dan harganya lebih murah. Bawang impor, beras impor, bahkan cabai pun kadang kalah saing dengan produk luar. Lalu siapa yang akan membeli hasil tani kami?
Saya dan banyak petani lain merasa semakin terpinggirkan. Anak-anak muda di kampung sudah banyak yang tak tertarik lagi bertani. Mereka melihat orang tua mereka bekerja keras sepanjang tahun, tapi hasilnya tak sebanding. Kalau tak ada perubahan, petani bisa benar-benar punah—bukan karena tidak mau bekerja, tapi karena tidak diberi kesempatan untuk sejahtera.
Saya tidak menolak modernisasi, tapi tolong libatkan petani dalam pengambilan keputusan. Kami tahu kondisi di lapangan lebih dari siapa pun. Kalau benar petani adalah pahlawan pangan, maka beri kami hak untuk hidup layak di tanah sendiri.