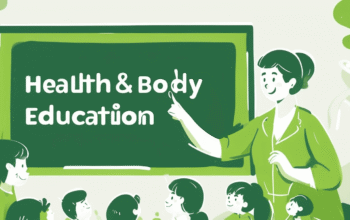Setiap libur semester, saya pulang ke kampung halaman di daerah Sulawesi. Tapi tahun demi tahun, kampung saya makin sepi. Rumah-rumah banyak yang kosong, sawah mulai terbengkalai, dan anak-anak muda nyaris tak ada. Mereka semua merantau ke kota—demi mencari kerja, sekolah, atau hanya karena “di kampung tidak ada masa depan.”
Fenomena ini bukan hanya terjadi di tempat saya. Di banyak wilayah lain di Indonesia, urbanisasi sudah menjadi semacam kewajaran. Kota besar seperti Jakarta, Makassar, dan Surabaya makin padat, sementara desa-desa justru kehilangan potensi manusianya.
Urbanisasi memang wajar terjadi dalam proses pembangunan. Namun yang jadi masalah adalah ketika proses ini tidak diimbangi dengan pemerataan ekonomi dan kesempatan. Kota tumbuh terlalu cepat, desa tertinggal terlalu lama. Akibatnya, kota menjadi sesak, muncul pengangguran baru, pemukiman kumuh, dan tekanan terhadap infrastruktur. Di sisi lain, desa kehilangan tenaga produktif dan menjadi stagnan.
Padahal, jika pemerintah serius membangun dari pinggiran seperti yang sering disuarakan, seharusnya desa-desa bisa menjadi pusat pertumbuhan baru. Potensi pertanian, pariwisata lokal, kerajinan, dan teknologi desa bisa dikembangkan jika ada dukungan modal, pelatihan, dan infrastruktur.
Anak muda di desa seharusnya tidak perlu merasa minder atau terpaksa pindah ke kota. Mereka bisa membangun usaha, membuka lapangan kerja lokal, dan bahkan memanfaatkan teknologi digital untuk terhubung ke pasar global. Tapi untuk itu, mereka butuh ekosistem yang mendukung: internet cepat, akses modal, pelatihan, dan pendampingan.
Urbanisasi bukan salah anak muda. Mereka hanya mencari peluang. Tapi sudah saatnya negara menciptakan peluang itu lebih merata. Agar kota tak harus menanggung beban sendirian, dan desa tak terus ditinggalkan.
Saya membayangkan suatu hari nanti, orang kota justru datang ke desa untuk mencari kesempatan—karena desa telah bangkit, hidup, dan memberi masa depan.